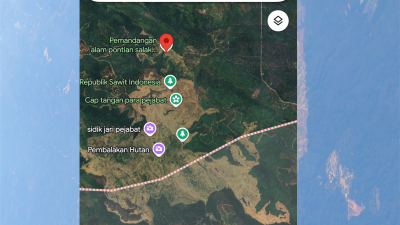Clara Alviony (Aktivis Dakwah)
 Opini — Setiap tanggal 10 Oktober, dunia seakan berhenti sejenak untuk memperingati satu isu yang kerap luput dari perhatian: kesehatan mental. Sejak pertama kali digagas oleh World Federation of Mental Health (WFMH) pada tahun 1992, Hari Kesehatan Mental Sedunia hadir sebagai pengingat bahwa kesehatan jiwa adalah fondasi penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Selain itu, World Health Organization (WHO) menegaskan, peringatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran global akan urgensi menjaga dan melindungi kesehatan mental.
Opini — Setiap tanggal 10 Oktober, dunia seakan berhenti sejenak untuk memperingati satu isu yang kerap luput dari perhatian: kesehatan mental. Sejak pertama kali digagas oleh World Federation of Mental Health (WFMH) pada tahun 1992, Hari Kesehatan Mental Sedunia hadir sebagai pengingat bahwa kesehatan jiwa adalah fondasi penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Selain itu, World Health Organization (WHO) menegaskan, peringatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran global akan urgensi menjaga dan melindungi kesehatan mental.
Tahun ini, peringatan tersebut mengusung tema “Mental Health at Work” atau Kesehatan Mental di Tempat Kerja. Bersama berbagai mitra, WHO menyoroti eratnya keterkaitan antara dunia kerja dan kondisi psikologis individu. Lingkungan kerja yang aman, suportif, dan manusiawi diyakini mampu menjadi tameng bagi kesehatan mental. Sebaliknya, situasi kerja yang tidak sehat berpotensi menjadi sumber tekanan, yang perlahan menggerus kepuasan kerja sekaligus menurunkan produktivitas.
Meski diperingati saban tahun, kesehatan mental tetap menjadi persoalan yang tak kunjung menemukan titik tuntas, baik di tingkat nasional maupun global. Realitas di lapangan justru menunjukkan gejala yang kian mengkhawatirkan. Di Indonesia, satu dari tiga anak berusia 10-17 tahun tercatat mengalami masalah kesehatan mental. Tak berhenti di situ, satu dari 20 remaja bahkan telah terdiagnosis gangguan mental dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Angka ini berarti lebih dari 15 juta anak dan 2,45 juta remaja tengah berjuang menghadapi beban psikologis yang serius, sebuah fakta yang sulit diabaikan.
Seperti Apa Seseorang yang Dikatakan “Sehat Mental” Itu?
Secara sederhana, dalam ilmu psikologi, sehat mental adalah kondisi ketika pikiran dan perasaan kita berada dalam keadaan tenang dan seimbang. Dengan mental yang sehat, seseorang bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih nyaman, menikmati hidup, serta mampu menghargai dan berhubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Orang yang sehat secara mental juga dapat mengenali potensi dirinya dan menggunakannya dengan baik untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Sebaliknya, ketika kesehatan mental terganggu, seseorang bisa mengalami perubahan suasana hati, kesulitan berpikir jernih, dan sulit mengendalikan emosi. Hal ini sering berdampak pada perilaku sehari-hari. Gangguan mental tidak hanya memengaruhi hubungan dengan orang lain, tetapi juga dapat menurunkan prestasi belajar dan produktivitas kerja. Masalah kesehatan mental sendiri bermacam-macam, namun yang paling sering dialami adalah stres, kecemasan, dan depresi.
Berdasarkan data dalam Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS), hasil kolaborasi Badan Litbang Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2022 bahwa kunjungan anak dan remaja ke biro-biro psikologi dilaporkan meningkat, mencapai 20-30%, menandakan bahwa krisis kesehatan mental bukan sekadar wacana, melainkan kenyataan yang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Survei I-NAMHS mencatat bahwa gangguan mental yang paling banyak dialami oleh remaja adalah gangguan kecemasan, khususnya kombinasi antara fobia sosial dan gangguan kecemasan, dengan prevalensi mencapai 3,7%. Setelahnya, gangguan depresi mayor (1,0%), gangguan perilaku (0,9%), gangguan stres pascatrauma (PTSD) serta gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (ADHD) masing-masing tercatat sebesar 0,5%. Lebih jauh, penelitian ini menyoroti beragam faktor risiko yang saling berkelindan dalam memengaruhi kesehatan mental remaja. Mulai dari perundungan, tekanan akademik di lingkungan sekolah, hingga dinamika relasi dengan teman sebaya dan keluarga. Selain itu, perilaku seksual berisiko, penyalahgunaan zat, pengalaman traumatis pada masa kanak-kanak, serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan mental turut memperparah kerentanan psikologis generasi muda.
Faktanya, pelayanan kesehatan mental di Indonesia masih berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Akses masyarakat untuk memperoleh bantuan di puskesmas terdekat kerap kali tidak mudah, bahkan terasa mahal dan tidak terjangkau di sejumlah wilayah. Ironisnya, belum seluruh puskesmas di Indonesia menyediakan layanan kesehatan mental. Keterbatasan ini terutama disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia yang terlatih dan memiliki kompetensi khusus di bidang kesehatan mental, sehingga kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya terlayani.
Apa Sih Penyebabnya?
Masalah kesehatan mental tidak muncul begitu saja. Apalagi sampai mengklaim bahwa seseorang “kurang kuat” atau “kurang bersyukur”. Karena persoalan kesehatan mental terbentuk dari mekanisme yang multifaktorial. Ada faktor dari dalam diri (internal), ada juga yang datang dari luar (eksternal).
Faktor internal, seperti faktor genetik, ketika ada riwayat gangguan kesehatan mental dalam keluarga, baik dari orang tua maupun keluarga. Faktor biologis, seperti ketidakseimbangan zat kimia di otak, cedera otak akibat benturan, epilepsi, atau gangguan saraf lainnya. Faktor psikologis, terutama pengalaman traumatis—mulai dari pelecehan, kekerasan, kecelakaan, kejahatan, hingga rasa kesepian berkepanjangan, isolasi sosial, atau pengalaman ditelantarkan di masa kecil. Paparan saat dalam kandungan, seperti alkohol, obat-obatan, atau zat kimia tertentu yang memengaruhi perkembangan otak. Riwayat penyakit tertentu, misalnya diabetes, yang juga bisa berdampak pada kondisi psikologis. Cedera fisik berat, khususnya benturan keras di kepala yang menyebabkan kerusakan otak.
Sedangkan faktor eksternal terdiri dari beberapa hal, seperti faktor keluarga punya peran besar. Pola asuh yang keliru, minimnya kelekatan emosional, hingga apa yang sering disebut sebagai “luka pengasuhan”, bisa meninggalkan bekas jangka panjang pada kesehatan mental seseorang. Belum lagi faktor sosiokultural, tekanan ekonomi, budaya yang serba menuntut, serta paparan media sosial yang tak henti-hentinya membandingkan hidup orang lain, ikut memperparah kondisi mental. Ditambah kebijakan negara di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang sering kali membebani rakyat: harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja semakin sempit, biaya pendidikan mahal, pengangguran meningkat, dan utang menjadi jalan keluar semu. Lebih jauh lagi, sistem kehidupan yang mengatur masyarakat saat ini juga tak bisa dilepaskan dari persoalan ini. Sistem sekuler-kapitalisme gagal menciptakan kehidupan yang menenangkan jiwa. Akibatnya, lahirlah manusia-manusia yang rapuh secara mental. Banyak orang, khususnya termasuk kaum muslim—akhirnya kehilangan arah, tak lagi memahami untuk apa hidup ini dijalani.
Sistem sekuler-kapitalisme pelan tapi pasti menjauhkan generasi muda dari nilai agama. Hidup diarahkan untuk “bebas sebebas-bebasnya”, menuruti hawa nafsu tanpa batas. Ketika sistemnya rusak, hasilnya pun ikut rusak—lahirlah generasi yang rapuh secara mental dan rentan mengalami gangguan kejiwaan. Dalam sistem yang memisahkan agama dengan kehidupan, tujuan hidup sering dipersempit, hanya terkungkung jadi soal materi: harta, jabatan, prestise, dan popularitas. Saat semua itu gagal diraih, banyak orang merasa tidak berharga dan tersingkir. Media sosial makin memperparah keadaan, bukannya produktif, platform digital justru sering menormalisasi kekerasan, perundungan, dan gaya hidup hedonis, sementara remaja dibiarkan tenggelam dalam arus tanpa filter. Di saat yang sama, kapitalisme melahirkan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Tekanan hidup makin berat, kecemasan meningkat, tapi semua dipaksa tetap terlihat “baik-baik saja”. Hidup akhirnya diukur pakai untung-rugi, seolah manusia cuma angka dan fungsi. Nilai kemanusiaan dan fitrah hidup pun perlahan diabaikan.
Menjadi Pribadi Sehat Mental di Tengah Tekanan dan Tantangan Sistem Kehidupan
Setiap muslim sejatinya harus punya visi hidup yang jelas, paham tujuan hidupnya, dan mampu melihat setiap peristiwa—baik yang datang dari luar maupun yang menimpa dirinya—dengan kesadaran dan ketenangan. Ujian hidup bukan sekadar kesulitan, tapi tanda cinta Allah pada hamba-Nya. Dengan kesabaran, setiap tantangan justru menjadi ladang pahala dan kesempatan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat.
Di sinilah pentingnya pendidikan dan pembinaan sejak dini. Fondasi pertama yang harus kokoh adalah akidah. Ketika akidah tertanam kuat, pola pikir dan sikap pun akan selaras dengan nilai-nilai Islam. Dari situ lahirlah muslim yang tangguh, cerdas, dan berakhlakul karimah—pribadi yang mampu menghadapi hidup tanpa kehilangan jati diri. Keluarga memegang peran krusial. Rumah seharusnya menjadi tempat anak-anak merasa aman, dicintai, dan nyaman—tempat mereka belajar ketenangan, keberanian, dan rasa percaya diri. Tak kalah penting, negara juga punya tanggung jawab: mengatur kehidupan bermasyarakat agar setiap manusia bisa menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi, dengan damai dan adil.
Negara seharusnya bukan cuma pengatur hukum atau ekonomi, tapi juga pelindung kesehatan mental warganya. Lingkungan yang sehat secara mental, pendidikan yang membentuk karakter, program rehabilitasi mental—semua ini seharusnya dijamin negara. Sejarah membuktikan hal ini bukan sekadar idealisme. Di masa peradaban Islam, misalnya, Dinasti Abbasiyah pada 705 M mendirikan rumah sakit lengkap dengan bangsal untuk penyakit jiwa di Baghdad. Ilmuwan muslim kala itu juga aktif meneliti dan menangani persoalan kesehatan mental.
Dalam perspektif Islam, negara bertindak sebagai raa’in, pengurus yang menjaga rakyatnya. Negara tidak hanya membentuk individu bertakwa secara personal, tapi juga mendorong mereka menjadi anggota masyarakat yang peduli, saling menguatkan, dan menjalin interaksi sosial berdasarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan. Allah Ta’ala berfirman, “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS Al-Maidah [5]: 2).
Dalam sistem pendidikan Islam menjadi fondasi utama: membentuk pola pikir dan sikap yang islami, menyiapkan generasi penerus peradaban, serta calon orang tua yang siap memikul tanggung jawab keluarga. Keluarga pun dijaga sebagai benteng utama, tempat anak-anak tumbuh dengan kasih sayang, aman, dan nyaman. Oleh karena itu, dalam sistem Islam, pendidikan tidak sekadar berorientasi pada transfer ilmu, tetapi bertujuan membentuk kepribadian Islam (syakhsiah islamiah) yang kokoh. Bersamaan dengan itu, pendidikan juga membekali individu dengan kecakapan berpikir dan bertindak agar mampu menghadapi, mengelola, serta menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan secara tepat.
Sistem ekonomi Islam mendukung kesehatan mental dengan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Kekayaan alam dikelola secara amanah agar manfaatnya merata. Dengan kebutuhan pokok terpenuhi, tekanan hidup yang sering memicu stres dan kecemasan bisa berkurang. Ibu dapat fokus mendidik anak tanpa terbebani mencari nafkah. Selain itu, negara juga bertindak sebagai junnah, pelindung moral dan mental rakyat. Media dan konten publik dikontrol agar tidak merusak akhlak atau mendorong gaya hidup permisif. Pelanggaran ditangani adil dan tegas, sehingga kesehatan mental dan moral masyarakat terjaga secara menyeluruh